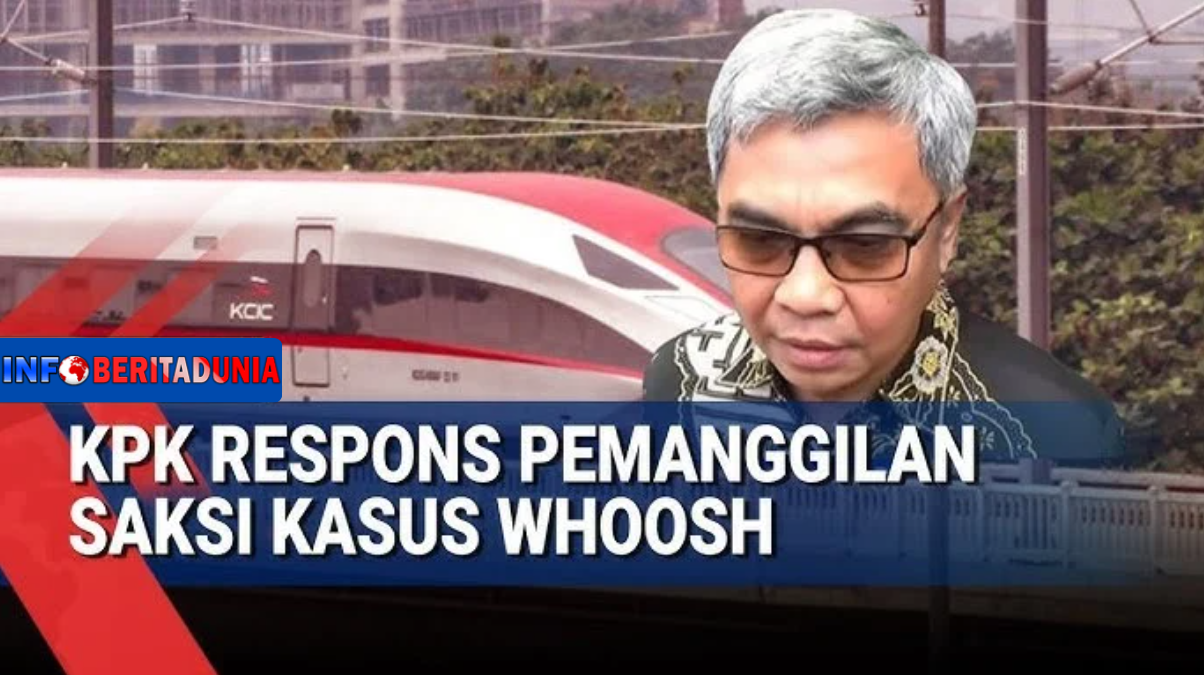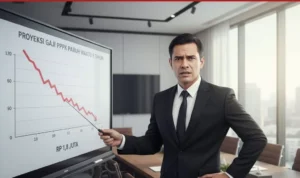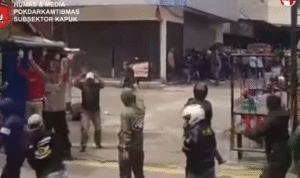POLEMIK seputar proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) kembali menyeruak ke ruang publik. Dugaan adanya praktik korupsi dalam proses perencanaan, pembiayaan, maupun pelaksanaannya kini menjadi bahan sorotan tajam.
Di tengah hiruk-pikuk itu, publik menunggu satu hal paling penting: bagaimana Presiden Prabowo Subianto menepati janjinya untuk tidak memberi tolerani praktik korupsi, bahkan bertekat mengejar pelakunya “hingga ke Antartika.”
Proyek Whoosh sejak awal memang ambisius. Ia digadang-gadang sebagai simbol kemajuan teknologi transportasi nasional.
Namun, di balik citra kemajuan itu, terselip problem klasik: transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan publik.
Biaya proyek yang semula diproyeksikan sekitar Rp 86 triliun, membengkak hingga lebih dari Rp 110 triliun, menimbulkan banyak tanda tanya.
Ketika pembengkakan anggaran tidak disertai dengan kejelasan mekanisme pertanggungjawaban, publik wajar mempertanyakannya.
Komisi Pemberantasan Korupsi mengaku tengah melakukan penyelidikan dugaan mark up proyek Whoosh sejak awal 2025.
Ujian integritas pemerintahan baru
Bagi pemerintahan Prabowo, kasus ini bukan sekadar isu proyek infrastruktur. Ia merupakan ujian terhadap komitmen politik hukum presiden dalam menegakkan keadilan dan memberantas korupsi tanpa pandang bulu.
Janji untuk membangun pemerintahan yang bersih dan kuat kini berhadapan dengan realitas kompleks: kepentingan ekonomi, politik, dan jaringan kekuasaan yang mengitarinya.
Prabowo dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa hukum tidak boleh “tajam ke bawah dan tumpul ke atas.”
Prinsip ini sejatinya merupakan aktualisasi dari konsep rule of law sebagaimana ditegaskan oleh A.V. Dicey, yaitu bahwa setiap orang, termasuk pejabat publik, tunduk pada hukum yang sama (Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, Oxford University Press, 1959).
Artinya, penegakan hukum dalam kasus Whoosh harus menembus batas kekuasaan dan kepentingan, jika ingin tetap berada di jalur konstitusional.
Korupsi dalam proyek publik bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam sila kelima Pancasila.
Dalam perspektif keadilan distributif Aristoteles, keadilan hanya akan hadir jika setiap orang memperoleh haknya secara proporsional, bukan berdasarkan kekuasaan atau kedekatan politik (Aristoteles, Nicomachean Ethics, Cambridge University Press, 2000).
Lebih jauh, dalam teori keadilan John Rawls, korupsi adalah bentuk ketidakadilan sistemik karena merusak asas kesetaraan peluang (fair equality of opportunity) dan menggerus kepercayaan publik terhadap institusi yang seharusnya menjamin keadilan (A Theory of Justice, Harvard University Press, 1971).
Karena itu, setiap tindakan korupsi pada proyek publik tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghancurkan tatanan moral dan keadilan sosial bangsa.
Dalam kerangka filsafat hukum utilitarianisme Jeremy Bentham, hukum harus diarahkan untuk mencapai the greatest happiness of the greatest number.
Korupsi justru menciptakan penderitaan kolektif dengan mengalihkan manfaat publik ke tangan segelintir orang (Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, Clarendon Press, 1907).

Maka, penegakan hukum yang konsisten terhadap kasus Whoosh merupakan bagian dari tanggung jawab moral negara untuk memastikan bahwa hukum tidak menjadi alat kepentingan elite.
Sebagaimana ditegaskan Satjipto Rahardjo, hukum tidak boleh menjadi a tool of power, melainkan harus menjadi a tool of social engineering alat untuk menata dan memperbaiki kehidupan masyarakat (Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, Genta Publishing, 2009).
Maka, jika penegakan hukum terhadap kasus Whoosh dilakukan dengan tegas dan transparan, ia akan berfungsi sebagai instrumen moral untuk memulihkan kepercayaan rakyat terhadap negara.
Menegakkan hukum, menjaga harapan
Dalam konteks politik hukum nasional, paradigma yang diperlukan bukan sekadar law enforcement, tetapi justice enforcement. Hukum tidak boleh berhenti pada penindakan formal, tetapi harus membawa pesan moral dan pembelajaran sosial.
Sejalan dengan itu, Lawrence Friedman menjelaskan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga komponen: struktur, substansi, dan kultur (Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, Russell Sage Foundation, 1975).
Kasus Whoosh akan menjadi ujian apakah ketiganya bekerja serentak: apakah struktur penegak hukum bebas intervensi, substansi hukumnya tegas, dan kultur hukumnya berani menegakkan keadilan, meski terhadap pihak yang berkuasa.
Penegakan hukum yang berkeadilan menuntut kejujuran dan keteladanan dari puncak kekuasaan.
Jika presiden benar-benar ingin menegakkan hukum tanpa pandang bulu, maka langkah pertama adalah memastikan independensi penyelidikan kasus Whoosh tanpa tekanan politik. Sebab, di sinilah letak tanggung jawab konstitusional dan moral seorang pemimpin.
Publik tidak menuntut kesempurnaan, tetapi konsistensi. Jika pemerintah berani membuka seluruh data, mengizinkan aparat penegak hukum bekerja tanpa intervensi, dan menyeret siapapun yang terbukti bersalah, maka ini akan menjadi momentum besar untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan pemerintahan.
Sebaliknya, jika kasus Whoosh berakhir seperti banyak kasus korupsi besar sebelumnya senyap di tengah jalan, maka janji “mengejar koruptor hingga ke Antartika” akan tinggal menjadi slogan politik tanpa makna moral.
Di sinilah Prabowo diuji apakah hukum di bawah pemerintahannya benar-benar menjadi panglima, atau sekadar pelengkap legitimasi kekuasaan.
Bila janji itu ditepati, sejarah akan mencatat bahwa pemerintahan ini berhasil menegakkan hukum tanpa kompromi. Namun jika tidak, rakyat akan kembali menyaksikan hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah.
Pada akhirnya, proyek Whoosh bukan hanya tentang transportasi cepat antarkota, tetapi juga simbol tentang seberapa cepat bangsa ini bisa bergerak menuju keadilan yang sesungguhnya.